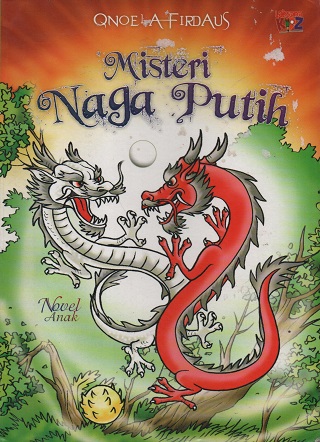Mitos tentang Sustainabilitas: Ruang Hidup Perempuan di Tengah Pusaran Tambang
Kamis, 25 Mei 2023 10:55 WIB
Proyek kendaraann listrik berbahan bakar energi bersih memang menawarkan solusi atas persoalan lingkungan yang kian mengkhawatirkan. Namun, bagaimana operasi produksi baterai kendaraan listrik berbahan baku nikel di tingkat akar rumput?
Misi Menyelamatkan Bumi
Pemerintah Indonesia menggaungkan tekadnya untuk ikut andil dalam upaya menjaga kenaikan temperatur bumi dan menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) global dengan berpartisipasi dalam Perjanjian Paris 2015. Pemerintah menunjukkan keseriusannya, salah satunya, melalui pengembangan ekosistem mobil listrik dan penggunaan energi terbarukan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim Ke-26 di Glasgow. Bukan sekadar kata tanpa makna, pemerintah kemudian merealisasikan komitmen itu dengan mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Sektor ini ditargetkan dapat berkontribusi mengurangi emisi karbondioksida sebesar 6,66 juta ton dari total pengurangan emisi yang ditargetkan pemerintah Indonesia yang sebesar 398 juta ton pada 2030.
Pengembangan ekosistem kendaraan listrik berbahan bakar energi bersih barangkali bisa menjadi pelipur ketakutan kita akan ancaman pemanasan global, mengingat sektor kendaraan bermotor yang umumnya menggunakan bahan bakar minyak berokan rendah merupakan salah satu penyumbang terbesar pencemaran udara dan emisi GRK, yaitu sebesar 27 persen menurut Climate Transparency Report 2020. Cukup masuk akal apabila pemerintah meyakini bahwa beralih ke kendaraan listrik, baik kendaraan pribadi maupun transportasi publik, dapat berkontribusi menurunkan emisi GRK dan mengurangi polusi udara yang dihasilkan sektor transportasi. Hal itu juga mengingat prospek pengembangan dan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia cukup prospektif, dimana angka penjualannya meningkat hampir 70 persen atau sebesar 395 unit pada 2021 dari yang hanya sebesar 121 unit pada 2020, sebagaimana data yang dirilis oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO). Hal itu juga didukung oleh melimpahnya cadangan nikel bahan baku baterai kendaraan listrik yang terkandung di dalam perut bumi Indonesia.
Alhasil, tidak heran apabila kini kita mulai terbiasa melihat kendaraan listrik berlalu lalang di jalanan Ibu Kota Jakarta, seperti bus listrik yang dioperasikan oleh PT Transjakarta dan sepeda motor listrik yang dinahkodai oleh perusahaan berbasis teknologi dan jasa transportasi Grab. Baru-baru ini, pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), juga menginisiasi program subsidi motor listrik yang digagas untuk mengakselerasi peralihan sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) ke motor listrik.
Akan tetapi, jauh dari hingar bingar kemeriahan narasi tentang energi terbarukan dan kendaraan listrik yang lebih banyak beredar di kota-kota besar dan hanya dinikmati oleh segelintir kelas menengah, kita akan menyaksikan pemandangan berbeda di rantai pasok terpenting baterai kendaraan listrik, yaitu di tingkat masyarakat sekitar tambang penopang proyek yang diklaim sebagai solusi atas permasalahan lingkungan itu.
Kolonialisme Gaya Baru dan Nestapa Tak Berkesudahan
Kendaraan listrik mungkin menawarkan jawaban atas permasalahan lingkungan yang kian mengkhawatirkan. Namun, proyek ini menyisakan isak tangis dan nestapa tak berkesudahan di tingkat akar rumput. Laporan WALHI yang bertajuk “Red Allert Ekspansi Nikel di Sulawesi” mengkonfirmasi bahwa praktik pertambangan nikel di Sulawesi menghasilkan dampak distruktif terhadap lingkungan dan menghancurkan basis kehidupan masyarakat lokal. WALHI mencatat bahwa sampai pada akhir 2021, sudah ada 293 Izin Usaha Pertambangan nikel yang diterbitkan di tiga provinsi di Sulawesi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Keseluruhan konsesi pertambangan nikel tersebut menguasai 639.302 hektar lahan atau setara dengan 66.9% dari total luas tutupan hutan berdasarkan klasifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karakteristik industri pertambangan yang rakus memakan lahan mengancam fungsi ekosistem hutan yang menjadi tumpuan hidup masyarakat serta rentan menghadirkan praktik penyerobotan lahan yang dilakukan berkat kongkalikong antara perusahaan, birokrat dan pemilik modal. Sebagai misal, beroperasinya perusahaan tambang nikel seperti PT Vale Indonesia berkontribusi menggerus tutupan hutan secara besar-besaran di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat ada seluas 41 ribu hektar lahan yang beralih fungsi sepanjang 2009 sampai 2020 di wilayah tersebut.
Dampak dari alih fungsi lahan untuk operasi pertambangan menuntun masyarakat lokal pada bencana sosio-ekologis yang lebih mematikan. Investigasi yang dilakukan WALHI juga menggarisbawahi maraknya kasus pencemaran di pesisir dan laut sekitar wilayah lingkar tambang akibat limbah sisa produksi nikel. Nelayan di Desa Lafeu di Sulawesi Tengah misalnya, mereka merasakan betul sulitnya menjaring ikan akibat pasokan ikan di laut mereka berkurang drastis setelah beroperasinya perusahaan tambang nikel. Padahal, di tahun-tahun sebelumnya, mereka dapat dengan mudah menangkap ikan, bahkan hingga mencapai berton-ton setiap harinya. Situasi serupa juga dihadapi oleh nelayan di Desa Torete di Sulawesi Tengah yang kini harus melaut lebih jauh untuk mendapatkan ikan. Padahal, sebelum perusahaan tambang nikel beroperasi pada 2010, mereka dapat dengan mudah menangkap ikan, bahkan ikan yang dibanderol dengan harga cukup mahal, seperti ikan putih dan ikan kakap merah. Contoh lainnya, masyarakat di Desa Lampia di Sulawesi Tengah, kini, tidak lagi dapat melakukan budidaya kepiting karena hutan mangrove tempat mereka menyandarkan hidup telah dirusak, bahkan hingga pada kedalaman 2 sampai 6 meter.
Ketiga fakta di atas hanyalah segelintir contoh kecil, mengingat operasi perusahaan tambang nikel di Indonesia masih menyisakan sejuta dosa-dosa yang menyengsarakan hidup masyarakat lokal. Praktik pertambangan lain seperti pembangunan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di Sumatera Selatan misalnya, juga telah menghadirkan bencana ekologis berupa banjir, pencemaran sungai, deforestasi, dan krisis air bersih yang merusak 1.010.054 hektar lahan milik masyarakat, menurut laporan WALHI pada 2018. Dampak destruktif itu belum lagi ditambah dengan kerugian ekonomi dan sosial akibat perampasan dan konflik lahan yang sepanjang tahun 2018 saja jumlahnya sudah mencapai 174 konflik.
Praktik industri pertambangan yang merajalela di Indonesia tidak ubahnya seperti struktur ekonomi ekstraktif yang dilancarkan oleh kolonial Belanda di negeri Hindia. Pada masa itu, eksploitasi sumber daya alam secara-besaran, baik yang ada di permukaan tanah maupun perut bumi, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Eropa melalui aktivitas ekspor bahan baku. Menempatkan suatu bangsa hanya sebagai penyedia bahan baku merupakan kata kunci untuk memahami praktik imperialism, sebagaimana yang didengungkan oleh Presiden Soekarno di pengadilan kolonial di Bandung pada 1930. Ditambah lagi, operasi industri ekstraktif rentan menyuburkan praktik korupsi yang operasionalnya memerlukan kerja sama erat tantara elit pemerintah, rezim lokal, perusahaan, dan para pemilik modal. Tidak jarang pula, aparat militer dikerahkan untuk mendukung kelancaran praktik pertambangan. Lagi-lagi, praktik semacam itu tidak berbeda jauh dengan strategi kolonial Belanda ketika menyuap pejabat desa dan melakukan penyerobotan lahan penduduk demi memuluskan operasi industri ekstraktif. Tidak berlebihan untuk menyebut bahwa saat ini kita sedang menghadapi kolonialisme gaya baru.
Nasib Ibu Bumi
Meskipun praktik pertambangan mengancam kelangsungan hidup seluruh masyarakat lokal, ada satu kelompok yang dua kali lebih berat memikul beban dan, karenanya, perlu mendapat perhatian lebih. Kelompok tersebut adalah perempuan. Para perempuan berkali-kali lipat menderita ketika alam mereka dirusak untuk menyuburkan praktik pertambangan. Terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang cenderung patriarkis, peran perempuan selalu diidentikkan dengan pekerjaan-pekerjaan domestik. Pekerjaan domestik itu erat sekali kaitannya dengan prinsip-prinsip kelestarian alam: memasak bahan makanan pokok, memastikan terpenuhinya kebutuhan air minum keluarga, memandikan anak, mencuci pakaian, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang bergantung pada sumber daya alam. Maka, ketika operasi industri tambang menghancurkan kelestarian alam, hal itu sama halnya dengan memiskinkan masa depan dan kehidupan perempuan. Pada akhirnya, para perempuan akan semakin terpinggirkan dari keintimannya dengan alam.
Eratnya hubungan antara perempuan dan alam digambarkan oleh Vandana Shiva, seorang ilmuwan-aktivis lingkungan dari India, melalui konsep ekofeminisme. Shiva menggabungkan konsep “ekologi” dan “feminisme” untuk melihat alam dan perempuan sebagai satu kesatuan yang sama-sama memiliki arti penting. Posisi perempuan dalam perspektif itu, menurut Shiva, adalah sebagai the sustenance perspective, yaitu aspek paling pokok bagi kehidupan. Perempuan dinilai sebagai pembawa kedamaian, keselamatan, dan kasih sayang. Sementara laki-laki, dalam pandangan Shiva, identik dengan karakter maskulin yang bercirikan persaingan, dominasi, penindasan, dan penghancuran. Tidak mengherankan bila kemudian kita sering sekali mendengar terminologi yang menunjukan intimasi hubungan antara perempuan dan alam, seperti “ibu pertiwi” dan “bumi adalah ibu” yang memaknai perempuan sebagai produsen kehidupan melalui alam.
Melampaui konsep ekofeminisme ala Vandana Shiva, nilai-nilai serupa sebenarnya juga dialami oleh perempuan dalam konteks kita sendiri. Kuatnya relasi antara alam dan perempuan itu digambarkan dengan jelas oleh para perempuan yang menjadi korban kebengesin operasi pertambangan. Informasi yang dihimpun WALHI di Desa Tapunggaya Sulawesi Tenggara, tempat beroperasinya PT MBG Nikel Indonesia, menemukan bahwa para perempuan tercerabut dari perannya sebagai penggerak ekonomi keluarga dan semakin terdomestifikasi sebagai ibu rumah tangga. Musababnya, hutan mereka tidak lagi subur bagi tumbuhnya daun nipa sebagai bahan baku tikar anyaman yang dapat mereka jual. Laut mereka yang tercemar juga membuat mereka tidak mungkin lagi melaut. Para laki-laki kini kebanyakan menjadi buruh di perusahaan, sementara perempuan, lagi-lagi, harus kembali ke ranah domestik sebagai ibu rumah tangga.
Sejurus dengan cerita itu, para perempuan di sekitar lubang tambang batubaru di PLTU Sumatera Selatan juga mengalami hal tak jauh berbeda. hancurnya potensi sumber daya alam membuat banyak perempuan tidak bisa lagi secara mandiri menyuplai bahan makanan pokok keluarganya. Mereka menjadi semakin konsumtif karena seluruh kebutuhan rumah tangganya harus dipenuhi dengan cara membeli—sesuatu yang membuat intimasi hubungan mereka dengan alam menjadi tercerabut. Tidak ada pilihan lain, sebab hancurnya alam membuat aktivitas bertani dan beternak menjadi tidak memungkinkan untuk dilakukan. Setelah alam mereka dijarah dan ruang hidupnya dirampas perusahaan tambang, posisi mereka sebagai perempuan juga dianggap tidak menguntungkan. Alih-alih mempekerjakan perempuan sebagai buruh, perusahaan lebih memprioritaskan pekerja laki-laki yang dinilai lebih cakap secara fisik dan nalar. Jika sudah demikian, kemanakah perempuan harus mencari makan?
Kebanyakan perempuan di area tambang kemudian terlempar menjadi pemulung yang memungut kepingan sisa-sisa batubara untuk kemudian dijual dengan harga sekitar Rp14.000 untuk setiap gerobaknya. Pekerjaan semacam itu bukannya tanpa risiko. Banyak di antara mereka yang mengalami kekerasan seksual, baik berbentuk pelecehan secara verbal, fisik, maupun psikologis. Selain itu, mereka juga harus berebut sisa-sisa tambang dengan truk pengangkut tanah galian batubara. Tidak jarang pula dari mereka yang mengalami kecelakaan hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, mereka tidak memiliki keberanian untuk menuntut ganti rugi kepada perusahaan atas kecelakaan yang mereka alami. Kita bisa melihat adanya relasi kuasa yang timpang ketika perempuan berhadapan dengan kepentingan bisnis-industri-kapitalisme.
Sustainabilitas untuk Siapa?
Potret kehidupan perempuan di area pertambangan nikel di Sulawesi dan pertambangan batubara di Sumatera hanyalah sebagian contoh kecil. Sepanjang sejarahnya, industri ekstraktif pertambangan selalu melemparkan masyarakat lokal ke dalam lubang penderitaan, alih-alih mendatangkan kesejahteraan sebagaimana yang dijanjikan oleh kepentingan bisnis-industri-kapitalisme. Dalam konteks ini, melihat dampak-dampak yang dirasakan perempuan melalui kacamata yang adil gender menjadi agenda super mendesak yang perlu kita lakukan. Tujuannnya adalah untuk memberikan keadilan pada kelompok masyarakat yang paling merasakan dampak operasi industri tambang, yaitu perempuan. Hal itu juga membentangkan jalan pada kita untuk mempertanyakan ulang, “Agenda sustainabilitas itu sebenarnya didengungkan para elit untuk melayani kepentingan siapa?” Bagi para perempuan yang hidup di sekitar tambang, narasi tersebut jelas hanyalah mitos. Alih-alih mendukung keberlanjutan masa depan bumi dan umat manusia, praktik pertambangan malah menimbulkan ketidakberlanjutan bagi kehidupan para perempuan. Apakah itu konsep sustainbilitas yang kita bayangkan? #LombaArtikelJATAMIndonesia
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Mitos tentang Sustainabilitas: Ruang Hidup Perempuan di Tengah Pusaran Tambang
Kamis, 25 Mei 2023 10:55 WIB

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0